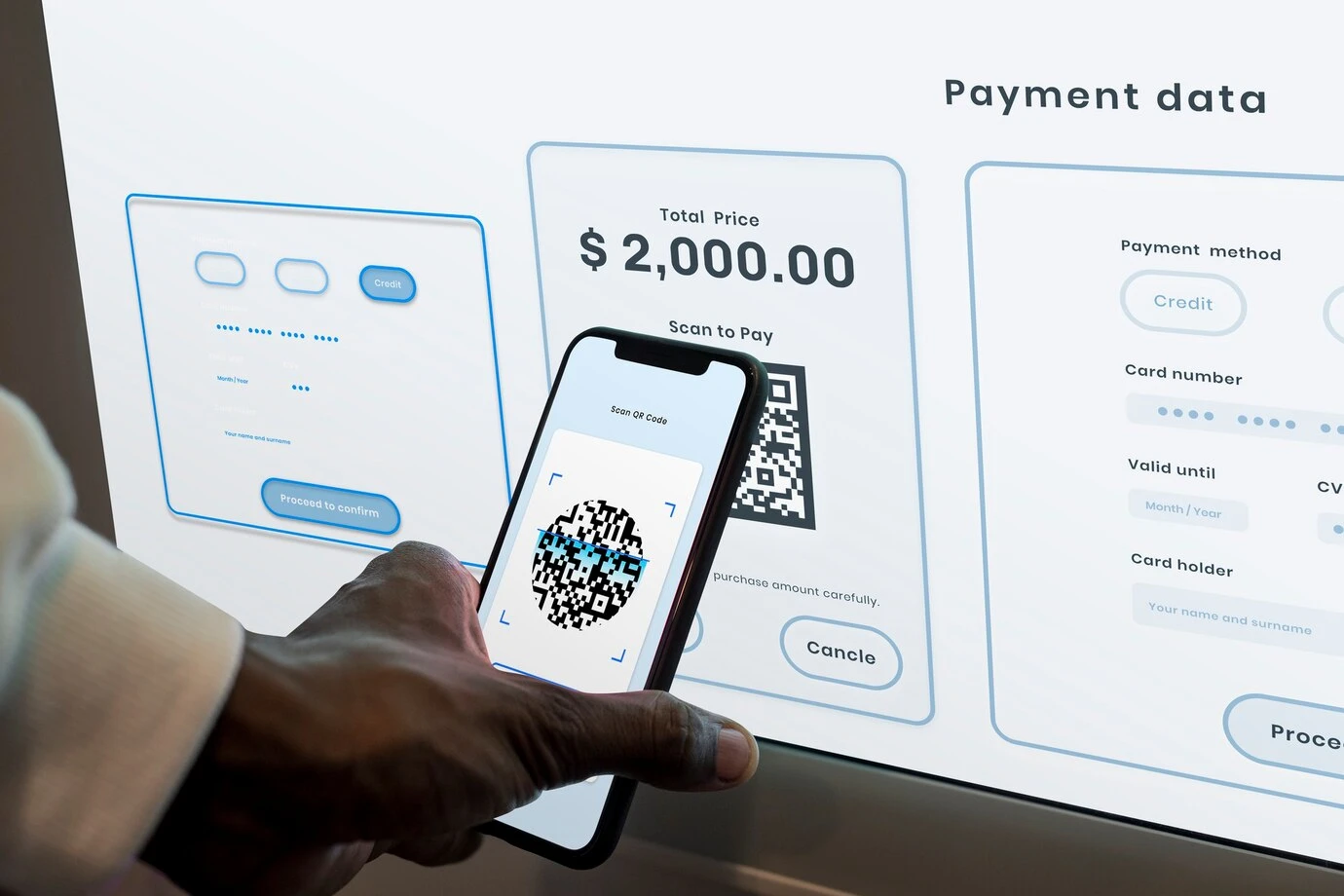Dalam era globalisasi ekonomi, transaksi lintas yurisdiksi menjadi praktik umum bagi perusahaan multinasional. Salah satu aspek penting dari interaksi ini adalah transfer pricing, yaitu penetapan harga atas transaksi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa. Meskipun legal secara normatif, transfer pricing memiliki potensi disalahgunakan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga mengurangi penerimaan pajak di negara sumber pendapatan.
Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menaruh perhatian serius terhadap praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran. Kegagalan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan dapat menimbulkan koreksi fiskal, sanksi administratif, bahkan sengketa hukum berkepanjangan. Artikel ini membahas dimensi hukum, risiko, tantangan implementasi, serta strategi kepatuhan yang relevan dengan kebijakan transfer pricing di Indonesia.
Transfer Pricing dalam Perspektif Regulasi Nasional dan Internasional
Transfer pricing menjadi isu internasional sejak berkembangnya praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) pada awal 1990-an. Untuk menanggulangi hal ini, OECD menerbitkan pedoman transfer pricing internasional (OECD Transfer Pricing Guidelines), yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia.
Di Indonesia, pengaturan transfer pricing merujuk pada beberapa regulasi utama, antara lain:
- Pasal 18 ayat (3) UU PPh: Memberi kewenangan kepada DJP untuk mengoreksi harga transaksi afiliasi yang tidak wajar.
- PER-22/PJ/2013: Mengatur kewajiban dokumentasi transfer pricing.
- PMK No. 213/PMK.03/2016: Mengatur Local File, Master File, dan Country-by-Country Report (CbCR).
- UU HPP Tahun 2021: Memperjelas sanksi administratif serta kerahasiaan data CbCR.
Menurut Darussalam dan Septriadi (2019), meskipun pendekatan arm’s length telah diadopsi penuh, tantangan lokal seperti keterbatasan data pembanding dan kapasitas fiskus menjadi hambatan implementasi yang nyata.
Baca juga: Apa itu CFC Rules dalam Kebijakan Anti-Penghindaran Pajak?
Penyebab Kegagalan dalam Pemenuhan Persyaratan Transfer Pricing
Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban transfer pricing umumnya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
a. Dokumentasi yang Lemah
Banyak perusahaan menganggap dokumentasi transfer pricing hanya sebagai formalitas. Penelitian oleh Yulianti & Nugroho (2020) menunjukkan bahwa dokumentasi dangkal sangat rentan dibatalkan dalam proses audit DJP.
b. Ketidaksesuaian dengan Prinsip “Substance Over Form”
Beberapa perusahaan menyusun kebijakan harga hanya berdasarkan kontrak tertulis, tanpa mencerminkan kenyataan bisnis (fungsi, risiko, aset). Hal ini bertentangan dengan prinsip OECD bahwa substansi ekonomi transaksi harus menjadi acuan utama.
c. Kesalahan dalam Pemilihan Metode Penilaian
Pemilihan metode seperti Transactional Net Margin Method (TNMM) sering dilakukan karena praktis, meskipun dalam beberapa kasus lebih tepat menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) atau Resale Price Method (RPM). Pemilihan metode yang salah dapat meningkatkan risiko koreksi fiskal.
Risiko dan Konsekuensi Hukum atas Ketidakpatuhan
a. Koreksi Fiskal
Jika DJP menemukan ketidakwajaran harga transaksi, maka laba kena pajak akan dikoreksi, berimplikasi pada meningkatnya kewajiban pajak.
b. Sanksi Administratif
Berdasarkan Pasal 13 UU KUP, wajib pajak dapat dikenakan bunga 2% per bulan atas kekurangan pembayaran, serta sanksi 50% atau 100% atas unsur kesengajaan.
c. Dampak Reputasi dan Sengketa Hukum
Sengketa transfer pricing yang terbuka di pengadilan dapat merusak reputasi perusahaan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kekalahan dalam sengketa terjadi karena lemahnya pembuktian dokumen dan substansi transaksi.
Tantangan Penegakan Transfer Pricing di Indonesia
a. Keterbatasan Data Pembanding
Ketiadaan pasar bebas dan transparansi dalam data transaksi domestik membuat benchmarking sulit dilakukan, baik oleh fiskus maupun wajib pajak.
b. Asimetri Informasi
Perusahaan multinasional umumnya memiliki akses lebih luas terhadap data global dan penasihat hukum internasional, sedangkan otoritas pajak bergantung pada sumber data lokal dan dokumen CbCR.
c. Tingginya Beban Pembuktian di Pengadilan Pajak
Dalam banyak kasus, DJP harus membuktikan koreksi fiskal yang dikenakan. Ketika dokumentasi audit tidak cukup kuat, sengketa kerap berpihak kepada wajib pajak.
Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kepatuhan
Agar terhindar dari risiko dan sanksi transfer pricing, perusahaan sebaiknya:
- Membangun Sistem Transfer Pricing Internal
Libatkan unit legal, akuntansi, dan pajak untuk menyusun kebijakan transfer pricing yang terdokumentasi, konsisten, dan sesuai substansi. - Melakukan Self-Assessment Berkala
Evaluasi kesesuaian metode dan hasil benchmarking sebelum terjadi pemeriksaan pajak. - Mengajukan Advance Pricing Agreement (APA)
Dengan APA, perusahaan dan DJP menyepakati metode harga transaksi afiliasi di awal, menghindari sengketa di masa depan. - Memperkuat Fungsi Tax Compliance
Tim pajak internal harus memahami bisnis secara komprehensif dan mampu menyusun dokumentasi yang sesuai prinsip arm’s length.
Baca juga: Mengenal Mutual Agreement Procedure, Solusi Sengketa Pajak Internasional
Dampak Makro terhadap Penerimaan Negara
Menurut Tax Justice Network (2021), Indonesia berpotensi kehilangan hingga USD 4,5 miliar per tahun akibat praktik transfer pricing yang agresif. Ini setara dengan sebagian besar belanja negara untuk sektor kesehatan atau pendidikan.
Transfer pricing bukan sekadar isu korporat, tetapi juga isu keadilan fiskal dan kedaulatan penerimaan negara. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, optimalisasi kepatuhan transfer pricing menjadi salah satu pilar penting dalam menuju kemandirian fiskal.
Kesimpulan
Transfer pricing merupakan isu strategis yang berada pada persimpangan antara pajak, hukum, dan tata kelola perusahaan. Ketidakpatuhan dalam menyusun dokumentasi atau menyimpang dari prinsip kewajaran dapat berdampak luas: koreksi fiskal, sanksi administratif, hingga risiko reputasi.
Dengan meningkatnya kerja sama internasional dalam pertukaran data (AEOI, BEPS), ruang untuk manipulasi harga transfer semakin sempit. Oleh karena itu, pendekatan reaktif harus diubah menjadi strategi proaktif: dokumentasi yang kuat, kebijakan berbasis substansi, serta koordinasi lintas divisi.
Sebagaimana ditegaskan oleh OECD (2022):
“Transfer pricing is not just a tax issue—it is a matter of corporate governance, transparency, and long-term sustainability.”
Perusahaan yang ingin bertahan dalam era akuntabilitas fiskal global harus menjadikan transfer pricing sebagai bagian dari strategi keberlanjutan bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif.
*) Penulis merupakan penerima beasiswa dari Pajakku. Seluruh isi tulisan ini disusun secara mandiri oleh penulis dan sepenuhnya merupakan opini pribadi. Tulisan ini tidak mencerminkan pandangan resmi Pajakku maupun institusi lain yang terkait.